Oleh : Kurnia Fajar*
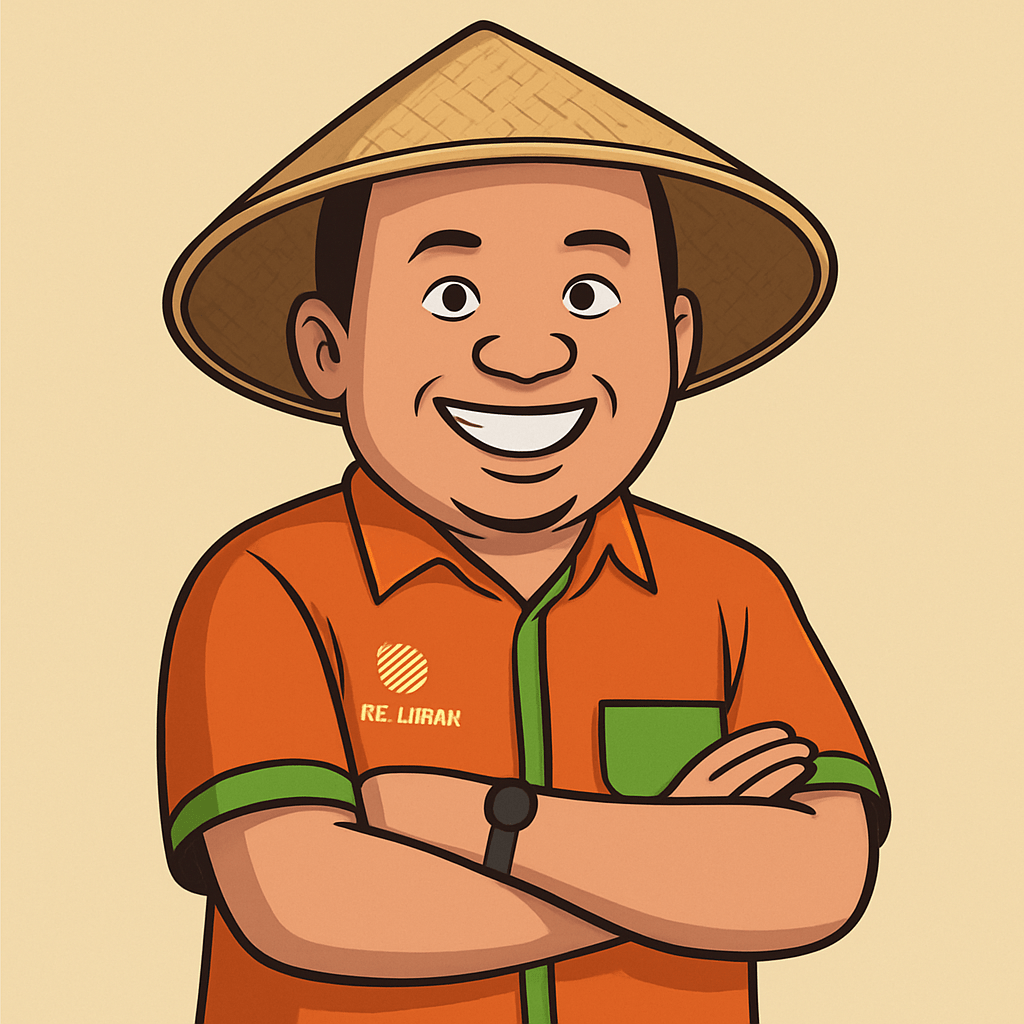
Saya, pertama kali menyukai musik adalah The Beatles, Queen dan Koes Plus. Dari kamar paman saya yang ketika itu berkuliah lagu-lagu itu selalu menemani sarapan. Musik erat kaitannya dengan rasa, membangun mood di pagi hari dan juga kontemplasi akan rasa di dalam jiwa. Kalau cinta itu soal rasa, maka lirik lagu adalah cara paling jujur untuk menyampaikannya—tanpa harus pakai caption ribet atau stiker love yang basi. Coba tengok dua lagu ini: Through the Fire dari Chaka Khan dan Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Satu diva soul 80-an dengan vokal yang meledak-ledak, satu lagi bintang muda Indonesia yang puitis dan mellow tapi manis. Dua generasi, dua benua, tapi ternyata, mereka lagi ngomongin hal yang mirip: cinta yang susah, ruwet, tapi tetap dicari. Cinta yang harus diperjuangkan, meskipun bentuk perjuangannya beda kayak siang dan malam. Dan yang bikin cerita ini makin renyah: konon Berharap Pada Timur lahir karena Salma terinspirasi langsung dari lagu Through the Fire. Dari kobaran Chaka, Salma menyalakan lentera kecilnya sendiri.
Dengerin Chaka Khan tuh kayak nonton adegan klimaks film romantis tahun 80-an—angin kencang, mata berkaca, dan dia teriak: “I’d gladly risk it all!” Lagu Through the Fire itu liriknya nggak main-main. Dia pake metafora besar kayak api, batas, tembok, dan ujung kabel (right down to the wire) untuk ngegambarin betapa seriusnya dia. Ini bukan cinta yang manja atau malu-malu, ini cinta yang siap nyemplung ke lahar gunung api kalau perlu. Kayak, “aku tahu kamu takut, tapi aku nggak. Aku yakin, dan aku akan kejar kamu sejauh apapun.” Heroik banget, kan? Chaka bukan cuma jatuh cinta, dia literally siap terbakar buat cintanya. Dan pengulangan frasa “through the fire” bukan cuma gaya, tapi semacam alarm emosi yang terus berdentang—semakin sering disebut, semakin terasa geloranya. Nah, beda cerita kalau kamu dengerin Berharap Pada Timur. Dari detik pertama, rasanya kayak lagi dengerin voice note panjang dari temen yang masih denial soal mantan—lirih, jujur, dan diam-diam nyesek. Lirik Salma itu nggak pakai api atau tembok, tapi cukup dengan helai rambut yang tertinggal dan topi hitam yang lupa diambil. Cinta di lagu ini nggak teriak-teriak, tapi justru bisik-bisik. Bukan tentang menerjang rintangan besar, tapi lebih ke berdamai sama ketidakpastian: “Kalau bukan kamu jalannya, ya aku bakal cari-cari beribu jalan lain.” Puitis banget, tapi juga penuh luka yang halus. Ini bukan cinta yang diteriakkan, tapi yang dinyanyikan dalam hati. Dan ternyata, meskipun benih lagunya ditanam dari lagu Chaka, Salma memilih menumbuhkannya jadi taman yang lebih sepi, lebih lokal, lebih merenung.
Menariknya, dua lagu ini sebenernya sama-sama ngomongin tentang “gimana kalau kita nggak bisa bareng?” Tapi cara mereka ngebahasnya beda total. Chaka Khan sangat yakin—dia siap all in, full send. Salma Salsabil justru ragu-ragu, penuh pertimbangan, sadar kalau dunia bisa aja nggak berpihak. Keduanya ngulang lirik beberapa kali, tapi tujuannya beda. Repetisi di Through the Fire tuh semacam mantra semangat: semakin diulang, semakin yakin. Sedangkan di Berharap Pada Timur, pengulangan jadi bentuk harapan yang rapuh, kayak ngomong ke diri sendiri biar tetap percaya walau hatinya goyah. Dan kalau kamu tahu inspirasi Salma datang dari Chaka, justru kamu bisa lihat betapa cerdasnya dia dalam “menjawab” lagu itu bukan dengan semangat yang sama, tapi dengan nada yang lebih diam dan reflektif.
Yang lebih menarik lagi, ini bukan cuma soal cinta antar pasangan—ini juga soal bagaimana perempuan bicara tentang cinta dari dua zaman berbeda. Chaka tampil sebagai tokoh utama yang berani, aktif, dan penuh keyakinan. Sementara Salma menulis sosok yang lembut tapi tidak kalah kuat—kuat karena berani menyimpan rasa dan tetap bertahan, walau harus sembunyi-sembunyi dari mata yang menilai. Dari vokal berapi-api ke bisikan lembut, dari power diva ke storyteller manis. Inilah evolusi cara perempuan mengekspresikan cinta: dulu harus membakar, sekarang cukup menyala pelan. Dan mungkin, dari semua perbedaan itu, satu hal yang paling indah adalah kesamaannya: bahwa cinta, sesulit apapun, tetap layak dilagukan—dalam kobaran api, atau dalam harapan yang mengarah ke timur.
Metamorfosisi musisi Indonesia lainnya lebih terasa di Ebiet G. Ade. Ia memulainya dengan cinta yang puitis dan satir. Lalu menutupnya tentang hidup yang kontemplatif, Kupu-kupu Kertas adalah magnum opus Ebiet. Sekaligus penutup. Kita tak akan menemukan lagi lirik-lirik dipenuhi simbol, yang bisa kita terjemahkan pada bab hidup apa saja. Kupu-kupu kertas tidak tentang hewan. Ia tentang serangga, dan serangga itu adalah kita. Ebiet memulai dengan rintihan. Tentang cinta, struggling, orang tua, isu-isu, tentang bencana. Ia telanjang, seperti kaki Camelia di Kintamani. Ebiet masih mencari. Belum menemukan. Pada Kupu-kupu Kertas, Ebiet tak lagi mencari. Dia menemukan. Camelia tak lagi sendirian di kamar. Dia berhenti menggugat. Di usianya yang tak lagi belia. Kupu-kupu Kertas, menurut pengakuannya, di temukan di malam setelah isya ketika Jakarta hujan dan orang-orang berebut tempat untuk pulang. Tapi betulkah pulang selalu ke tempat dari mana kita pergi? Atau pulang bisa ke mana saja, sebab kilau cahaya masih memukau
*)Gerilyawan Selatan
